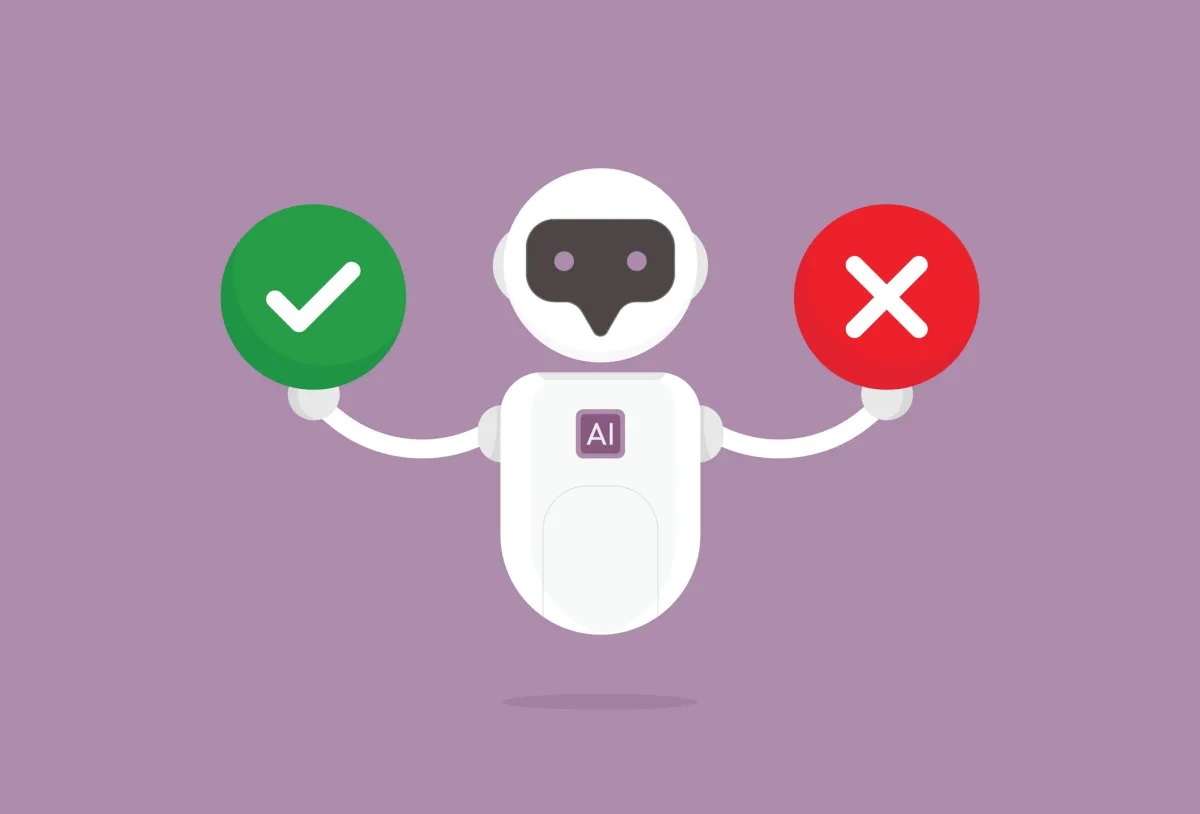Seorang pembelajar dengan semangat: Rogo, Scribo, Gratias Ago (Aku Bertanya, Aku Menulis, Aku Bersyukur). Pernah bekerja di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Titik Lemah AS dalam Perang Tarif Trump
Sabtu, 3 Mei 2025 17:35 WIB
Dunia sibuk merespon retorika tarif Trump, namun lupa bahwa ketergantungan AS pada ekspor jasa merupakan titik lemah AS yang sangat rentan.
***
Saat Presiden Donald Trump memicu gelombang perang tarif, dunia terguncang oleh pendekatan unilateralis yang menargetkan hampir semua mitra dagang utama Amerika Serikat. Setidaknya 180 negara terdampak, baik langsung maupun tidak langsung.
Dari Cina hingga Kanada, dari Uni Eropa hingga Indonesia, negara-negara harus memilih antara retaliasi atau kompromi. Namun, dalam hiruk-pikuk respons terhadap kebijakan proteksionis ini, satu hal luput dari sorotan: dominasi Amerika di sektor jasa, yang justru menyimpan kelemahan strategis yang serius bagi Washington.
Trump membingkai perang tarif sebagai perjuangan "menyeimbangkan perdagangan" dan mengembalikan manufaktur Amerika. Namun, narasi ini menyesatkan karena hanya berfokus pada perdagangan barang.
Padahal, sektor jasa menyumbang lebih dari 70% PDB Amerika dan menjadi motor utama ekspor bersih negara tersebut selama lebih dari satu dekade. Saatnya negara-negara yang terdampak tarif Trump sadar, bahwa di balik slogan "America First" tersembunyi kenyataan bahwa justru Amerika lah yang menikmati keuntungan besar dalam perdagangan jasa global.
Menurut Bureau of Economic Analysis, ekspor jasa AS mencapai US$1,1 triliun pada 2023, dengan surplus sekitar US$300 miliar. Bila dihitung melalui pendapatan anak perusahaan AS di luar negeri, angka tersebut bisa meningkat hingga US$2 triliun.
Ini mencakup jasa teknologi, konsultan manajemen, keuangan, hak cipta, royalti perangkat lunak, hingga sektor pendidikan dan pariwisata.
Sementara AS terus mencatat defisit dalam perdagangan barang (mencapai US$1,2 triliun pada tahun yang sama), sektor jasa tetap menjadi penyeimbang utama neraca eksternal AS.
Dengan kata lain, surplus jasa adalah kartu truf ekonomi yang selama ini tidak banyak disentuh oleh lawan dagang AS. Hal yang ironis bukan? Mengingat Trump dan tim ekonominya kerap mengeluhkan ketimpangan neraca dagang secara keseluruhan, namun hanya pada sisi barang.
Yang menarik, sebagian besar ekspor jasa AS bersifat tak kasat mata dan sulit dikenakan tarif secara konvensional. Mahasiswa asing, turis, langganan perangkat lunak, dan royalti hak cipta tidak mudah diukur secara langsung. Namun, pengaruh ekonomi dan geopolitik dari dominasi jasa AS sangat nyata.
Retaliasi Asimetris: Mengapa Dunia Perlu Menargetkan Sektor Jasa
Retorika Trump memang cukup ampuh. Seolah menghipnotis dunia, reaksi beragam dan cenderung spontan. Padahal, berdasarkan logika "reciprocal tariffs" yang digunakan tim ekonomi Trump, negara-negara yang mengalami defisit jasa dengan AS secara teoritis memiliki justifikasi untuk melakukan pembalasan.
Dengan logika yang sama, studi oleh Simon Evenett dan Fernando Espejo dari Global Trade Alert menunjukkan bahwa negara-negara yang menerima lebih banyak ekspor jasa dari AS dibandingkan yang mereka ekspor barang ke AS sebetulnya “berhak” mengenakan tarif ekspor jasa AS.
Negara Brasil misalnya, dalam studi itu disebutkan, bisa memberlakukan tarif balasan atas impor jasa dari AS sebesar 148%, Tiongkok bisa memberlakukan tarif jasa 70%. Kanada dan Swiss masing-masing bisa menerapkan tarif jasa sebesar 32% dan 31%.
Meski perhitungannya tidak mudah, namun fakta yang sangat jelas adalah fund manager seperti BlackRock, konsultan seperti McKinsey, dan raksasa perangkat lunak seperti Microsoft—merupakan salah satu ekspor jasa AS yang sangat bergantung pada pasar internasional.
Perlu diakui, respons semacam ini memang belum pernah muncul dalam riuh perang tarif Trump saat ini, kecuali China yang sempat melarang beredarnya film Holywood dan melarang industri mereka menggunakan jasa perbankan AS.
Dunia masih berpikir dalam kerangka konvensional: membalas tarif barang dengan tarif barang. Padahal justru pada sektor jasa lah AS paling rentan. Di sinilah kelemahan strategis Amerika seharusnya menjadi target koreksi sistemik.
Bagaimana dengan Indonesia?
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia selama ini cenderung pasif dalam mengidentifikasi leverage dalam perundingan dagang.
Ketika AS memberlakukan tarif tinggi atau mengancam kebijakan non-tarif, respons kita sering terjebak pada negosiasi satu arah: menambah impor dari AS, memberi kelonggaran regulasi, atau menghapus hambatan pasar.
Namun, dengan memahami titik lemah AS di sektor jasa, Indonesia sebetulnya bisa mengubah strategi. Mumpung masa penundaan 90 hari masih berlaku.
Pemerintah Indonesia dapat mulai memprioritaskan penyedia jasa lokal untuk proyek infrastruktur strategis. Meski lagi-lagi terkendala SDM, tidak berarti langkah ini tak bisa dilakukan.
Kita juga dapat memperketat persyaratan lisensi bagi perusahaan konsultan asing, hingga meninjau kembali sistem pajak digital untuk raksasa teknologi AS seperti Google, Apple, dan Meta.
Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga menyesuaikan praktik kita dengan negara-negara lain seperti Prancis, Jerman, atau bahkan India yang telah lebih dulu mengambil tindakan. Setidaknya, Indonesia dapat memulai langkah kolaborasi dengan negara lain selain AS.
Kita juga dapat menuntut akses teknologi dan kemitraan strategis yang lebih adil, terutama dalam ekonomi digital, pendidikan tinggi, dan sektor kreatif, melalui konten negosiasi asimetris: membalas kebijakan tarif Trump dengan meminta akses tersebut. Jika tidak terjadi kesepakatan, Indonesia dapat membalas dengan tarif tinggi atau dengan berbagai pembatasan terkait impor jasa AS.
Dalam konteks globalisasi, fakta berbicara bahwa nilai perdagangan jasa jauh melampaui nilai perdagangan barang. Dan di sanalah seharusnya kita menyusun narasi ekonomi baru: dari negara pengekspor bahan mentah atau produk-produk low economic value menjadi pemain jasa bernilai tinggi.
Trump memang telah berhasil menanamkan narasi bahwa Amerika adalah korban sistem perdagangan global. Dunia seolah menerima ini begitu saja, dan justru terburu-buru mencari cara untuk menenangkan kemarahan Washington. Padahal, surplus perdagangan jasa AS adalah bukti bahwa sistem ini sangat menguntungkan mereka.
Saatnya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya mulai membangun narasi tandingan yang cerdas dan strategis. Retaliasi di sektor jasa bukanlah tindakan agresif, tapi koreksi yang adil dalam sistem yang timpang.
Negara sebesar Indonesia memiliki sektor digital dan ekonomi kreatif yang terus tumbuh, hendaknya menjadi pelopor dalam mendefinisikan ulang kesetaraan dalam perdagangan jasa.
Arsitektur perdagangan global ke depan tampaknya akan berubah. Ketika dunia masih terpaku pada perang tarif produk (barang) seperti baja dan kedelai, tekstil dan sebagainya, saatnya Indonesia menata ulang kekuatan ekonomi yang sesungguhnya—yaitu memperkuat kontribusi sektor jasa ke ranah seperti: teknologi informasi, pengetahuan, kecerdasan buatan, pusat data, hak cipta, bahkan seni dan kebudayaan.
Trump mungkin tetap akan bersikukuh dengan agenda agresifnya, namun kali ini, dunia seharusnya tidak hanya bersiap membalas dengan “lagu lama”—yaitu tarif komoditas dibalas dengan tarif komoditas yang lebih tinggi.
Saatnya negara-negara dunia, termasuk Indonesia, mengumandangkan “lagu baru” yang lebih “merdu”, yang membuat AS terpaksa harus mengakui dominasinya saat ini di sektor jasa dan berhenti menjadi “korban” dari proteksionisme mitra dagangnya dan perdagangan bebas yang dianggapnya “tidak adil”.
Jika kita benar-benar ingin menghadirkan perdagangan global yang adil, maka sudah waktunya dunia menantang dominasi jasa Amerika—sektor yang selama ini dibiarkan tak tersentuh—dengan melakukan retaliasi asimetris dengan menargetkan sektor jasa yang selama ini menggerakkan ekonomi AS.
Dalam panggung ekonomi global, kekuatan tersembunyi bukan berarti tak bisa disentuh. Justru di sanalah titik paling rawan. Bagi Amerika Serikat, sektor jasa adalah benteng emas yang rapuh — dominan, namun telanjang.
Jika dunia ingin membalas secara cerdas, maka di sinilah “urat nadi” perdagangan dengan AS yang layak ditekan. Tidak ada negara, sekuat apa pun, yang pantas kebal dari konsekuensi. Keadilan global tidak bisa dijadikan tuntutan sepihak — ia harus dibayar dengan perilaku yang adil pula.
Sebuah prinsip yang sebetulnya sederhana, bukan?
Pemerhati Kebijakan Industri dan Perang Dagang
0 Pengikut

Manuver AS di Tengah Gencatan Tarif Trump
Selasa, 20 Mei 2025 09:21 WIB
Senjata China dalam Perang Tarif Trump
Senin, 12 Mei 2025 17:08 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0


 Berita Pilihan
Berita Pilihan






 98
98 0
0